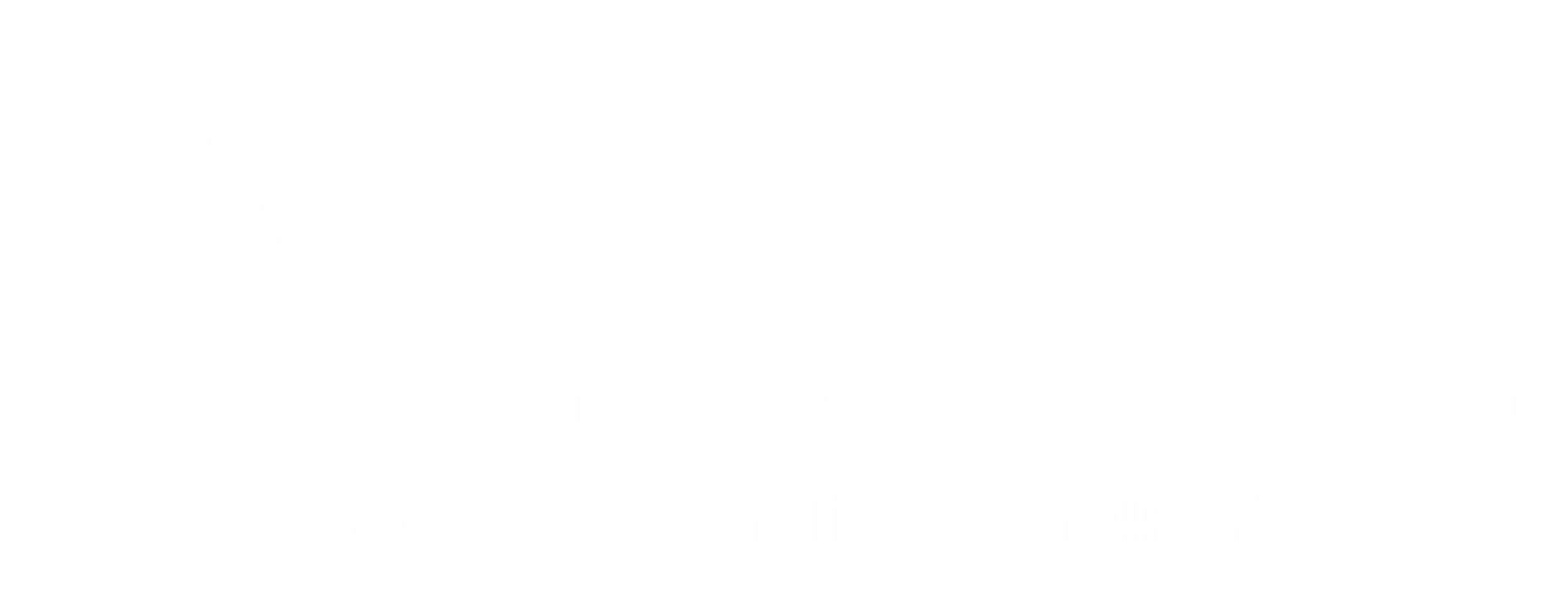Judul : Belajar Dusta di Sekolah Kita
Penulis : Sucipto Hadi Purnomo
Foto Cover : Siddiq Sumakna
Penerbit : Gigih Pustaka Mandiri, Yogyakarta
Tahun : April, 2008
Pancaindera
merupakan sebuah nikmat Tuhan yang tak terkira. Melalui pancainderalah
kita belajar menyikapi fenomena yang terjadi dalam lingkungan. Begitu
pula dengan Sucipto hadi Purnomo. Dia gunakan pancainderanya untuk
mengamati carut marut dunia pendidikan Indonesia. Lantas dia ikat hasil
pengamatannya tersebut dalam buku ini.
Buku ini sengaja disajikan
bagi dunia pendidikan Indonesia yang tak jua bangkit dari keterpurukan.
Begitu peliknya permasalahan sehingga sulit mengurai satu persatu akar
masalah yang ruwet bagaikan benang layang-layang. Melalui buku ini
pulalah Sucipto mencoba mengurai akar masalah tersebut. Sadar atau tidak
pendidikan Indonesia telah mengalami pergeseran dari cita-cita
sebenarnya.Sekolah sebagai tempat formal untuk memanusiakan manusia kini
telah bermutasi menjadi ladang bagi kapitalis-kapitalis pendidikan.Guru
tak lebih layaknya buruh dan siswa merupakan komoditas yang
menguntungkan para kapitalis tersebut.
Mentalitas kapitalisme yang licik telah merasuk ke dalam pejabat
pendidikan hingga kepala sekolah. Kenyataan ini tak bisa kita pungkiri.
Beberapa daerah di pelbagai pelosok negeri busung korupsi ini dikabarkan
membutuhkan banyak tenaga kependidikan. Ironis jika hal tersebut ada
sedangkan banyak sarjana pendidikan yang menganggur. Pemerintah tak bisa
tinggal diam begitu saja membaca kenyataan ini lantas mereka merekrut
guru bantu. Dengan perekrutan guru bantu, kebutuhan pemerintah
terpenuhi. Angka pengangguran para sarjana pendidikan setidaknya dapat
diminimalisir. Kenyataan berbicara lain, honor perbulan guru tersebut di
bawah rerata UMR buruh pabrik. Guru bantu tak sekadar membantu
pemerintah memenuhi tetapi lebih tepatnya menjadi guru (pem-)bantu.
Beban tugas banyak bahkan melebihi guru PNS, tetapi honor berbanding
terbalik dengan profesionalitas mereka. Sungguh tak pantas jika
pemerintah mengklaim telah mengangkat kesejahteraan guru (hlm. 22).
Pengangkatan guru bantu bukan untuk menyejahterakan guru,melainkan demi
kepentingan pemerintah dalam pengadaan guru karena tak kuat (tak mau?)
mengangkat guru negeri (hlm.16).
Kurikulum sebagai acuan
operasional diobok-obok tak karuan. Ganti menteri ganti kurikulum, bukan
hal baru bagi rakyat. Rakyat bisa memaklumi hal tersebut, tokh para
menteri juga ingin menunjukkan prestasinya, bukan? Tuntutan standar
kelulusan nasional merupakan wujud pengkhianatan kurikulum tingkat
satuan pendidikan yang pemerintah gulirkan. Pendidikan yang seyogyanya
menjadi tempat siswa mengembangkan kompetensinya hanya tersentuh sebatas
ranah kognitif. Pencapaian target nilai angka menjadi acuan
keberhasilan proyek mercusuar pemerintah ini. “Gengsi gede-gedean”
menjadi sebuah pertaruhan sekolah dengan orangtua. Wajar jika akhirnya
sekolah mengajarkan dusta kepada anak didiknya. Sekolah agaknya lebih
banyak menuntut daripada mendengarkan. Para guru sering lebih bangga
ketika anak didiknya mampu mempersembahkan nilai 100 ketimbang mereka
yang tak bisa menuntaskan PR ( hlm. 30).
Untuk mencapai
kompetisi bergengsi tersebut, LKS (Lembar Kerja Siswa) menjadi
alternatif pilihan. Bejibun PR yang membebani siswa terjadi karena
fungsi LKS tersebut. Sekian beban tersebut menjadikan LKS sebagai Lembar
Kesengsaraan Siswa. LKS telah memberangus keceriaan anak-anak. Bahkan
tak sedikit terjadi kongkalikong pemerintah,penerbit, bahkan guru dalam
pengadaan LKS ini. LKS menjadi sebuah proyek semesteran atau tahunan
sebagai komoditi menambah finansial guru. Kalaulah Kurikulum tingkat
satuan pendidikan tak mampu menyingkirkan LKS,kalaulah para kepala dinas
pendidikan tak mampu menyurutkan jual-beli lembaran ini di sekolah,
entah dengan apalagi kita bisa menyurutkan subyek didik dari
lembaran-lembaran menyengsarakan itu ( hlm.58). Harus bagaimana lagi,
membuat LKS adalah usaha sampingan guru untuk menambah kebutuhan
keluarga dan membayar hutang di bank.
Margaret Mead
berkata,”Nenek melarangku sekolah,jika ingin menambah pengetahuan”.
Artinya selama ini sekolah tidak dapat menjadi lahan pengetahuan.
Sekolah tak lebih hanyalah tempat formal mendapat ijazah sebagai syarat
masuk jenjang selanjutnya. Barangkali setelah membaca kumpulan essay
yang cukup provokatif ini, timbul sikap apatis seperti neneknya
Margaret. Oleh karena itu membaca buku ini harus benar-benar dengan hati
yang bersih untuk melihat segalanya dari berbagi sisi. Kumpulan essay
yang terkumpul dalam buku ini diharapkan dapat membuka hati dan
pandangan pemerintah dan masyarakat terhadap dunia pendidikan Indonesia
yang kian tak menentu ini. Satu hal yang pasti, sekolah tak pernah salah
dan kalah. Sekolah tak lebih tak kurang adalah sebagai candu! Selalu
Diburu ( hlm.6)
Peresensi : Estu Pitarto
* Penulis adalah pegiat Komunitas Wedangjae